Itjen KKP terus berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program prioritas KKP melalui pengawasan dan pendampingan https://t.co/5EVRShRR76
— Itjen Kuat KKP Hebat (@itjen_kkp) February 10, 2026
 Majalah Sinergi Edisi I Tahun 2025
Majalah Sinergi Edisi I Tahun 2025
Halo Pembaca setia, Buletin Sinergi...I
Ditengah kebijakan efisensi anggaran belanja K/L, kami tetap setia terbit untuk menyampaikan warta pengawasan intern dalam rubrik reportase, kilas lensa dan auditoria, serta gagasan/ide seputar pengawasan intern. Berikut kami sampaikan edisi khusus flipbook Buletin Sinergi edisi I Tahun 2025 sebagai sarana informasi dan komunikasi seputar pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Buletin ini berisikan artikel-artikel menarik seputar pengawasan intern Inspektorat Jenderal periode Tahun 2025, antara lain:
Silahkan kunjungi dan baca Buletin lengkap pada link berikut:
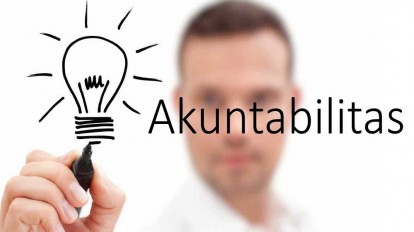 Implementation of ERP in AKIP Evaluation System
Implementation of ERP in AKIP Evaluation System
Reformasi Birokrasi di Indonesia terus bergulir memasuki fase ketiga 2020-2024. Pada masa ini pemerintah menargetkan tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima [1]. Salah satu area birokrasi yang menjadi fokus perubahan adalah akuntabilitas kinerja. Penyelanggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia telah dimulai sejak era reformasi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP, hingga terakhir ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKIP. Melalui perangkat kebijakan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban dari setiap Instansi Pemerintahan untuk melaksanakan dan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.
Penyelenggaraan SAKIP di Indonesia dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). MENPAN RB terus berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman tentang implementasi SAKIP yang baik sebagai bentuk penerapan manajamen kinerja pada sektor pemerintahan, sekaligus melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP diumumkan kepada publik secara nasional setiap tahunnya.
Evaluasi atas implementasi SAKIP pada K/L atau Pemda merupakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki mekanisme kinerja. Terdapat standar minimal yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah akuntabel dengan cara menyesuaikan kondisi organisasi dengan template Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang telah disiapkan oleh MENPAN RB. Adapun komponen yang menjadi penilaian SAKIP sesuai Peraturan MENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, terdiri atas: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Mekanisme evaluasi AKIP dikelompokkan dalam beberapa tahapan, yaitu pendokumentasian, analisis, interpretasi dan informasi yang diperlukan alam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian Evaluasi AKIP, sedangkan metode evaluasi AKIP menggunakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.
Disamping melakukan penilaian langsung pada K/L dan Pemda, MENPAN RB memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L dan Pemda untuk melakukan evaluasi AKIP pada internal organisasi guna mewujudkan pengendalian internal yang lebih memadai pada instansi pemerintahan. Maka, MEMPAN RB memberikan template LKE untuk dapat digunakan dalam proses evaluasi. Dengan berpedoman kepada template LKE tersebut, maka APIP di seluruh K/L dan Pemda telah melaksanakan evaluasi AKIP sebagaimana mestinya, termasuk juga APIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet, APIP KKP melakukan inovasi teknologi dalam evaluasi AKIP, hal ini dikarenakan tools template LKE yang digunakan dari MENPAN RB berupa perangkat lunak (file) jenis microsoft excel yang telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan. Pada dasarnya, penggunaan tools ini tidak memiliki kendala teknis yang terkait dengan unsur validitas dan akurasi data dalam penilaian, namun kekurangannya adalah lebih kepada aspek teknis pelaksanaan evaluasi yang belum terintegrasi, kecepatan dalam memperoleh data evaluasi, serta proses analisis dan kompilasi hasil evaluasi pada sembilan unit eselon I merupakan pekerjaan yang tidak sederhana untuk mendapatkan nilai prediksi pada tingkat kementerian. Adanya keterbatasan tools penilaian tersebut, menjadi alasan bagi APIP KKP mengembangkan sistem aplikasi berbasis website yang memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi AKIP (e-AKIP) dapat bekerja secara otomatisasi dan terstruktur dalam kerangka sistem Enterprise Resource Planning (ERP), sehingga dapat mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan kualitas hasil yang memuaskan.
sumber: http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/telematika/article/view/7949
 Paradigma Analisis Kebijakan Publik Dalam Audit Kinerja
Paradigma Analisis Kebijakan Publik Dalam Audit Kinerja
Kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah rangkaian tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa peraturan, program, atau proyek yang diterapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memecahkan masalah sosial, ekonomi, atau politik yang dihadapi oleh negara (Moran & Rein, 1978).
Audit kebijakan publik di Indonesia merupakan suatu proses evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Audit kebijakan publik dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan, implementasi, dan hasil dari kebijakan publik, serta untuk mengevaluasi kinerja dari organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan (Fischer, 2007).
Di Indonesia, audit kebijakan publik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan pemeriksaan atas keuangan negara. BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pengawasan kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Salah satu contoh kebijakan publik yang di audit oleh BPK adalah program pemberian bantuan sosial. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana bantuan sosial, serta mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hasil audit tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan program bantuan sosial agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sendjaja et al., 2018).
Selain itu, audit kebijakan publik juga dilakukan dalam bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan proyek-proyek besar lainnya. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana proyek, serta mengevaluasi efektivitas pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, audit kebijakan publik juga dilakukan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Secara keseluruhan, audit kebijakan publik merupakan suatu proses yang penting dalam pengelolaan negara. Proses ini dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dikeluarkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar kebijakan tersebut dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sendjaja et al., 2018).
Selain itu, audit kebijakan publik juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara serta dalam pengelolaan dan pengawasan kebijakan publik.
Kontekstualisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan sebuah organisasi pemerintah yang dibentuk untuk mencapai target-target tertentu di bidang kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bijaksana (KKP, 2022).
Visi KKP adalah “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Kemudian, mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: (1) Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; (3) Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan (RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024, 2020).
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, ditetapkanlah tujuan, program, serta kegiatan yang dirumuskan menjadi Rencana Strategis dalam periodesasi tertentu. Selanjutnya, perencanaan tersebut diturunkan menjadi Sasaran Strategis dan dijabarkan ke dalam IKU dan IKK sampai dengan unit kerja terbawah. Keseluruhan proses tersebut merupakan alur penetapan kebijakan publik yang tentunya harus menerapkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Fase perumusan kebijakan dikembangkan oleh para ahli menjadi siklus kebijakan yang dianggap standar dan berurutan yaitu policy adoption; policy assessment; policy adaptation; policy succession dan policy termination (Fischer, 2007).
Dewasa ini, terjadi perubahan paradigma Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara maju, semula menerapkan New Public Management (NPM) menjadi Public
Value Management (PVM) (Pollitt & Bouckaert, 2017).
NPM adalah suatu pendekatan manajemen yang diterapkan di sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. NPM menekankan sistem manajemen desentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan (controlling) dan perbandingan (benchmarking) untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah yang baik (Good Governance) sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari NPM adalah untuk memperbaiki kualitas efisiensi dan efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta mendorong penerapan good governance (Pollitt & Bouckaert, 2017).
Di sisi lain, PVM merupakan pendekatan manajemen yang diterapkan di sektor publik untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. PVM menganggap bahwa tujuan dari sebuah organisasi publik adalah untuk menciptakan nilai publik (public value) bagi masyarakat, yang dapat diukur melalui kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. PVM menekankan pentingnya pengelolaan aset organisasi dan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan nilai publik. PVM juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama. PVM mengutamakan pengelolaan yang berbasis pada data dan analisis, dan menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. PVM juga mengutamakan pengelolaan strategis yang berfokus pada masa depan, dan menempatkan pengukuran kinerja dan akuntabilitas sebagai komponen penting dari proses manajemen (Moore, 2012).
Secara historis, PVM merupakan penyempurnaan dari konsep NPM. Sistem ini menekankan pada pentingnya peningkatan value pada society/public melalui output dan outcome dari aktivitas layanan publik oleh pemerintah. Sedangkan kesempurnaan public value tercapai bila suatu kebijakan dapat menerjemahkan dan menselaraskan harapan-harapan yang berbeda dari masyarakat. Di titik inilah kebijakan publik menjadi sarana untuk mengagregasi kepentingan masyarakat.
Audit kinerja dapat menerapkan metode analisis kebijakan publik untuk menilai kinerja entitas, khususnya pada aspek efektivitas, dengan cara melakukan komparasi antara kondisi di lapangan dengan kebijakan yang berlaku. Auditor menguji tingkat kesesuaian antara implementasi dengan kebijakan. Oleh karena itu, penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Dari pengukuran tersebut akan didapat kesimpulan apakah suatu kebijakan telah gagal atau berhasil memberikan nilai tambah kepada masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan.
Tahap ex-ante merupakan tahap menilai suatu proses perumusan kebijakan dari agenda setting sampai tahap akhir (termination atau evaluation), baik dari proses, alasan, tujuan, aktor-aktor
pembuat kebijakan dan penetapan aktor-aktor yang bertanggungjawab dalam implementasi suatu kebijakan (Aisyiah & Ahzar, 2017). Sedangkan tahap ex-post adalah tahap menilai output dan outcome serta merumuskan simpulan atas kinerja entitas dengan menilai relevansinya dengan kebijakan yang digunakan (Narsa, 2011).
Apabila mencermati dokumen PKPT Itjen tahun 2022 terdapat dua tujuan pengawasan intern oleh itjen, yaitu (Inspektorat Jenderal KKP, 2022):
Berdasarkan dokumen PKPT tahun 2022, Itjen masih menempatkan pengawasan pada umumnya dan audit pada khususnya, sebagai pengawalan terhadap pelaksanaan kinerja KKP agar efektif dan efisien. Audit dilakukan secara parsial pada unit kerja tertentu dan belum mengacu pada keselarasan proses perumusan sampai dengan dampak dari kebijakan publik yang ditetapkan oleh KKP. Aktifitas audit masih berkutat pada masalah temuan 3E, kelemahan sistem akuntansi, kelemahan sistem pengendalian, dan kerugian negara. Audit masih belum difungsikan sebagai proses penilaian keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan organisasi.
Kesimpulan
Pemahaman yang baik atas profil dan fungsi utama suatu entitas sangat penting bagi auditor dalam merumuskan rekomendasi konstruktif yang andal bagi entitas dalam audit kinerja. Dalam menilai kinerja sebuah entitas, auditor mengidentifikasi kedalaman entitas dalam membuat kebijakan pengembangan public value demi pencapaian kinerja pelayanan publik dan pemenuhan tuntutan kebutuhan publik. Objek pemeriksaan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka tata kelola kebijakan publik yang berbasis pada keselarasan program kerja dari tingkat atas sampai paling bawah. Objek pemeriksaan di tingkat Eselon I dan II menjadi lebih relevan untuk dilakukan audit kinerja, sedangkan unit kerja dibawahnya yang bersifat teknis menjadi objek pemeriksaan sampling untuk diuji perannya sebagai pelaksana.
Audit kinerja dengan paradigma analisis kebijakan publik dapat menjadi salah satu tahapan dalam fase penyusunan kebijakan, yaitu fase policy assessment, yang dapat memberikan rekomendasi apakah suatu kebijakan publik masih harus diteruskan karena berhasil, atau dicabut karena gagal dalam mengatasi masalah yang terjadi.
Daftar Pustaka
 Akuntabilitas Pengelolaan Kas Pada Bendahara Pengeluaran
Akuntabilitas Pengelolaan Kas Pada Bendahara Pengeluaran
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga antara lain.
Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan dilingkungan kementerian/Lembaga setelah memperoleh persetujuan dari perjabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
Pengakuan: Kas dan setara kas diakui pada saat:
Penerimaan kas melalui rekening Kementerian Negara/Lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas kementerian Negara/Lembaga. Pengeluaran kas melalui rekening/kas Kementerian Negara/Lembaga diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh Bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas Kementerian Negara/Lembaga.
Pengukuran: Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.
Penyajian: Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
Pengungkapan: Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah mengungkapkan:
Perlakuan Khusus
Temuan BPK-RI atas Kas pada Bendahara:
Tabel 1. Saldo Kas di Bendahara Pengeluarab yang belum disetorkan ke RKUN
|
No |
Satker |
Saldo UP (Rp) |
Saldo TUP (Rp) |
|
1 |
567481- Stasiun KIPM Palembang |
90,00 |
- |
|
2 |
567812- Balai KIPM Jayapura |
9.949.506,00 |
2.123.630,00 |
|
3 |
403817- LRSDKP Bungus |
- |
2.306.760,00 |
|
4 |
427692- PPN Brondong |
- |
119.500.000,00 |
|
Sub Jumlah |
9.949.596,00 |
123.930.390,00 |
|
|
Jumlah |
133.879.986,00 |
||
Sisa UP/TUP tersebut seharusnya disetorkan ke RKUN paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Namun demikian, BP baru menyetorkan pada bulan Januari 2022. Adapun rekomendasi BPK-RI atas temuan tersebut, sebagai berikut:
Temuan Inspektorat Jenderal pada Laporan Hasil Audit Kinerja, terdapat temuan hasil pemeriksaan fisik pengelolaan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran, diketahui sebagai berikut:
Dalam rangka pengelolaan kas yang lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
Daftar Pustaka
 Sistem Integritas Nasional
Sistem Integritas Nasional
Komisi Pembesantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun belakangan mencanangkan sebuah gagasan yang sangat baik untuk berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi yang dimulai dari pembangunan integritas individu, kelompok, organisasi bahkan secara nasional. Gerakan tersebut dikenal dengan pembangunan Sistem Integritas Nasional. Heru Prasetyo, Indonesia Bussines Link, Resourse Centre for Coorporate Citizenship (2018), menyebut tema ini sebagai “Prevention is a big undertaking (Pencegahan adalah upaya besar)”. Gagasan tersebut dituangkan ke dalam rencana aksi dalam kerangka Sistem Integritas Nasional (SIN).
Sejalan dengan waktu, gerakan Sistem Integritas Nasional juga menyentuh kepada KKP. Pada awalnya sebelum adanya nomenklatur SIN, KKP telah melaksanakan pembangunan integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31 Tahun 2016 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu melakukan penguatan integritas yang mana pada masa ini yang dianggap menjadi penyebab terjadinya tindakan korupsi karena lemahnya sistem dan penegakan hukum, serta rendahnya integritas sumber daya manusia, (KKP 2016).
Kewenangan merumuskan kebijakan Pembangunan Integritas di lingkungan KKP dibebankan kepada Inspektorat Jenderal KKP melalui Inspektorat V yang mulai membangun zona-zona integritas pada unit-unit kerja pelayanan publik untuk diarahkan untuk menjadi wilayah yang terbebas dari paktek-praktek KKN sejak tahun 2013, dan terus berkembang sehingga manghasilkan model pembangunan Sitem Integritas yang dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada dasarnya, pembangunan Sistem Integritas di lingkungan KKP juga merupakan tindakan dan upaya-upaya pencegahan terhadap risiko adanya praktek-praktek KKN di lingkungan KKP. Tidakan pencegahan dalam perspektif pengawasan intern tersebut dilakukan melalui kegiatan konsultansi (Advisory Service) yang pada prakteknya juga merupakan kegiatan-kegiatan pengawasan untuk kemudian menghasilkan saran, himbauan atau rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini sesuai dengan kententuan bahwa Kegiatan Advisory adalah kegiatan konsultansi yang bertujuan untuk memberikan saran/rekomendasi peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan terhadap proses pengendalian dan penanganan risiko (Peraturan Irjen KKP 318, 2021) dalam hal: a) Memberi saran atas desain/rancangan pengendalian; b) Memberi saran dalam membangun kebijakan dan prosedur; c) Memberi saran pemecahan masalah pada kegiatan yang berisiko tinggi; dan d) Memberi saran pada aktivitas-aktivitas tertentu manajemen risiko organisasi.
 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern
Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2021 dalam Standar Audit AAIPI, 2110: menyebutkan bahwa Tata Kelola Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam: a) Membuat keputusan strategis dan operasional; b) Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian; c) Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi; d) Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi; e) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan f) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asurans lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja.
Sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola pengawasan intern di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Tata Kelola Pengawasan Intern sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan Nilai Tambah dan melindungi aset bagi pencapaian tujuan Kementerian, sejalan dengan prioritas nasional, dan dinamika perubahan lingkungan, dan disebutkan lebih lanjut pada ayat (3) bahwa yang dimaksud memberikan Nilai Tambah dan melindungi aset bagi pencapaian tujuan Kementerian berbunyi: Pengawasan Intern yang meningkatkan Nilai Tambah dan melindungi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan, diantaranya pada huruf d: “memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Kementerian”.
Pengaturan lebih lanjut tentang struktur penyusunan rekomendasi, tatacara terbitnya rekomendasi dan mekanisme tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan terdapat pada Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 318 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola pengawasan intern di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara konseptual disebutkan pada pasal Bab II, pasal 3 ayat (1): Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan melindungi aset untuk mencapai tujuan Kementerian, pengawasan intern dilaksanakan dengan: Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP dan proses tata kelola Kementerian (huruf d, 2021).
Dari beberapa tinjauan literasi dan regulasi diatas, jelas menempatkan rekomendasi hasil pengawasan sebagai salah satu produk penting dalam proses bisnis pengawasan intern yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan organisasi, namun dengan catatan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Untuk menghasilkan rekomendasi yang baik harus memenuhi kaidah teknis yang tepat (Peraturan Irjen KKP 318, 2021) menyebutkan pada pasal 36: “Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), harus bersifat konstruktif untuk menghilangkan penyebab dan akibat, serta mendorong perbaikan SPIP, dengan memperhatikan: a) Penyampaian pesan yang penting dan jelas; b) Realistis dan dapat ditindaklanjuti; c) Pertimbangan waktu pelaksanaan rekomendasi; d) Personil yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rekomendasi; dan e) Estimasi terhadap potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi.
 Internal Audit Pada Sektor Publik
Internal Audit Pada Sektor Publik
Internal Audit didefinisikan sebagai kegiatan konsultansi dan penjaminan yang independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola (IIA, 2009). Sejalan dengan pengertian tersebut, (COSO, the implementation of the Framework, 2013) menyatakan bahwa “Strong internal control can help mitigate many of the risks associated with such complex pressures. According to COSO, the implementation of the 2013 Framework “is expected to help organizations design and implement internal control in light of many changes in business and operating environments, broaden the application of internal control in addressing operations and reporting objectives, and clarify the requirements for determining what constitutes effective internal control.” (Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mengurangi banyak risiko terkait dengan tekanan kompleks seperti itu. Penerapan pengendalian internal diharapkan dapat membantu organisasi merancang dan mengimplementasikan pengendalian internal mengingat banyak perubahan dalam bisnis dan lingkungan operasi, memperluas penerapan pengendalian internal dalam menangani operasi dan tujuan pelaporan, dan memperjelas persyaratan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan pengendalian internal yang efektif.”)
Pada dasarnya, pengawasan memiliki tujuan ekonomi yang penting dalam melayani masyarakat, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memperkuat kepercayaan diri terhadap kualitas pelaporan keuangan (Institute of Audit Chartered in England and Wales, 2005). Sejalan dengan waktu, bentuk layanan pengawasan di seluruh dunia berevolusi sesuai kebutuhan pada zamannya. Pada zaman revolusi industri yang terjadi pada kurun waktu abad ke 18, dikatakan bahwa pengawasan hanya berbentuk verifikasi, yaitu untuk menilai kejujuran suatu transaksi (Lee Teack heang dan Azham Ali, 2008), namun seiring dengan waktu hingga saat ini telah bermunculan berbagai bentuk pengawasan sesuai dengan perkembangan jenis transaksi ekonomi di dunia sehingga melahirkan istilah yang melekat pada kegiatan pengawasan saat ini yaitu audit. Jenis audit terus berkembang dari audit kepatuhan, audit keuangan, audit kinerja, audit sosial, audit teknologi informasi, hingga layanan konsultansi untuk peningkatan kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (Reading dan Sobel, 2009).
Kehadiran unit-unit pengawasan internal pada sektor korporasi dan sektor publik atau Pemerintahan memiliki peran dalam menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Perkembangan peran pengawasan internal lebih luas sejalan dengan perkembangan konsep Manajemen Risiko dan Pengawasan Berbasis Risiko. Kehadiran Pengawas Internal untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi melalui efektivitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern (IIA, 2009), dengan target yang diharapkan adalah (Reading dan Sobel, 2009): a) Operasi organisasi yang efisien dan efektif; b) Keandalan sistem informasi dan pengambilan keputusan yang berkualitas hasil dari sistem tersebut; c) Keamanan asset; dan d) Kepatuhan terhadap kebijakan, kontrak, peraturan dan regulasi. Pendekatan pengawasan (audit approach) telah mengalami evolusi yang dapat dibagi ke dalam empat kategori yaitu (1) Control-based Auditing, (2) Process-based Auditing, (3) Risk-based Auditing, dan (4) Risk Management-based Auditing (Sobel, 2015). Perbedaan keempat pendekatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.
Perkembangan Pendekatan Audit
Sumber : Paul Sobel, 2015
| Control Based | Process Based | Risk Based | Risk Management |
|---|---|---|---|
| Tujuan : Menilai kepatuhan terhadap peraturan, hukum, atau regulasi | Tujuan : Menilai efisiensi dan efektivitas proses kegiatan dan dihubungkan dengan pencapaian tujuan | Tujuan : Menetapkan risiko kunci dan menilai efektivitas pengendalian dalam memitigasi risiko apakah telah mencapai tingkat yang dapat diterima | Tujuan : Menetapkan tujuan, risiko, penilaian risiko, dan toleransinya, dan mengevaluasi efektivitas aktivitas manajemen risiko dalam mendukun pencapaian |
| Fokus : Mengidentifikasikan dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan kepatuhan | Fokus : Mengidentifikasikan gap antara proses yang dilaksanakan dengan best practices | Fokus : Mengidentifikasikan pengendalian yang tidak beroperasi secara efektif dalam memitigasi risiko kunci hingga ke tingkat yang dapat diterima | Tujuan : Fokus : Mengidentifikaasikan gap antara tingkat efektivitas manajemen risiko yang ada dan diinginkan |
| Pengujian : Menggunakan pengujian substansi dan prediksi statistik, walaupun dimungkinkan penggunaan pengujian kepatuhan | Pengujian : Evaluasi berfokus pada perbandingan best practices dengan yang dilaksanakan, dengan sebagian melakukan pengujian kepatuhan untuk mengevaluasi proses yang dilaksanakan | Pengujian : Kombinasi pengujian substansi dan kepatuhan, namun fokus pada risiko kunci | Pengujian : Kombinasi pengujian substansi dan kepatuhan, tergantung tingkat efektivitas manajemen risiko yang dirancang |
| Rekomendasi : Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan | Rekomendasi : Menghubungkan gap dengan tujuan organisasi/ kegiatan dan mengurangi dampak gap | Rekomendasi : Menghubungkan penyimpangan dan kesalahan dengan risikonya, serta menyediakan | Rekomendasi : Menghubungkan gap pada efektivitas manajemen risiko |
 Pengawasan Internal Pemerintah di Indonesia
Pengawasan Internal Pemerintah di Indonesia
Sejarah keberadaan unit pengawasan internal di Indonesia sudah dimulai sejak era VOC (1608 – 1800) dan Pemerintahan Hindia Belanda (1800 – 1939), dengan adanya Algemene Rakenkamer et Indie (Dewan Pengawas Keuangan) yang melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap pengelolaan keuangan Negara yang dikelola Pemerintah Hindia Belanda (Balk, Van Dijk, dan Kortlag diterjemahkan oleh Gaastra, Niemeijer, dan Koenders, 2007). Selain itu, Regering Accountantdist (1936) di bawah Pemerintahan Hindia Belanda merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan melakukan pemeriksaan atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu (Bijblad No 13731, 1936). Pasca kemerdekaan Indonesia, Algemene Rakenkamer berubah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan (Surat Penetapan Pemerintah no 11/OEOM, 1946), dan Regering Accountantdist berubah menjadi Kantor Djawatan Akuntan dengan fungsi yang sama sebagaimana pada era Pemerintahan Hindia Belanda. Bentuk pengawasan internal mulai berkembang pada tahun 1968 ketika Kantor Djawatan Akuntan Negara yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) melakukan audit keuangan (opini) terhadap BUMN.
Pada Tahun 1983, DJPKN bertranformasi menjadi BPKP melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dan bertanggungjawab terhadap pengembangan berbagai jenis kegiatan pengawasan pada sektor Pemerintahan antara lain pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus, pemeriksaan aspek strategis dan pemeriksaan komprehensif (1996). Adapun pasca reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dalam pengawasan keuangan negara. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang ini memberi garis pemisahan yang semakin jelas antara peran pengawas eksternal pemerintah dan pengawas internal pemerintah. Peran Pengawas eksternal dilaksanakan secara mutlak oleh BPK RI, sedangkan peran pengawas internal dijalankan oleh BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten yang memiliki keterkaitan hubungan kerja antara unit kerja pengawasan internal pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008.
Namun demikian, meskipun adanya perbedaan ruang lingkup pengawasan tersebut, BPKP beserta APIP lainnya sama-sama menjalankan fungsi pengawasan internal melalui lima jenis pengawasan (2008), yaitu Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya. Hanya saja, selain memberikan konsultansi atas penguatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern, BPKP memperoleh mandat lebih dalam hal pembinaan dan peran konsultansi untuk mengarahkan K/L/D mempedomani standar dalam penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) disamping BPKP juga melakukan pembinaan terhadap penguatan tingkat kapabilitas APIP di seluruh Indonesia.
 Probity Audit, Mengawal Pengadaan Barang/Jasa
Probity Audit, Mengawal Pengadaan Barang/Jasa
Pengawalan pengadaan barang/jasa dilakukan Audit Probity. Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.
 Whistleblowing System KKP
Whistleblowing System KKP
Jika Anda selaku Pegawai di lingkungan KKP (ASN/Non ASN), melihat atau mengetahui dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan ASN KKP, laporkan ke Tim Penanganan Pengaduan KKP. Jika laporan anda memenuhi syarat/kriteria, maka akan diproses lebih lanjut. Kunjungi website WBS KKP sekarang.
Definisi Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi di lingkungan KKP yang melibatkan pegawai dan orang lain, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku. WBS adalah media untuk menampung segala bentuk pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup KKP. Istilah whistleblower dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola ataui olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Dalam tulisan ini, istilah “peluit peluit “ diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada public mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.
Pengelolaan aplikasi WBS ini berada pada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kriteria Pengaduan yang baik dan benar harus memenuhi beberapa unsur:
Berikut ini akan diuraikan beberapa langkah-langkah dan alur yang dilakukan ketika akan menyampaikan pengaduan kepada kami, mohon dibaca secara seksama:
 Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
Tata kelola merupakan kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Tata kelola memiliki keterkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian intern. Aktivitas tata kelola yang efektif mempertimbangkan risiko pada saat menyusun strategi. Sebaliknya, manajemen risiko didasarkan pada tata kelola yang efektif (misalnya, tone at the top, selera risiko dan toleransi risiko, budaya risiko, dan pengawasan manajemen risiko). Tata kelola yang efektif juga bergantung pada pengendalian intern dan komunikasi efektivitas pengendalian‐pengendalian tersebut kepada manajemen. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.
